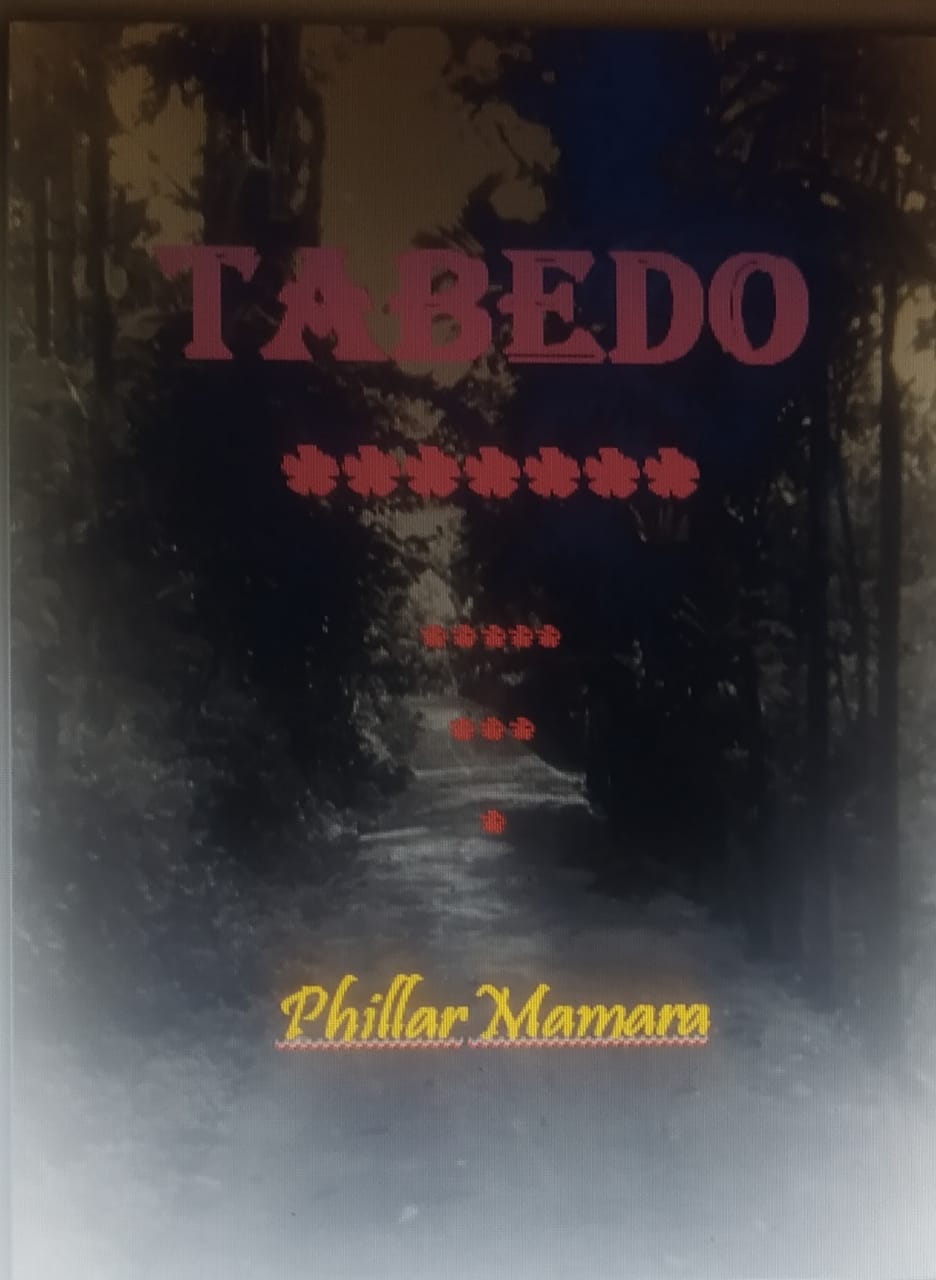Tabedo – Bagian 31
Oleh: Phillar Mamara
Kira-kira pukul setengah tiga dinihari Vitlan tersentak dari tidurnya. Ia bangkit, beranjak ke pintu dan membukanya. Suasana gelap di luar kamar. Ia ingin ke kamar mandi mengambil wudhuk untuk melaksanakan shalat tahajjud, tapi dibatalkannya. Tak mungkin rasanya meraba-raba dinding ke sana ke mari untuk menemukan saklar lampu.
Pintu kamar ditutup kembali. Vitlan duduk bersandar ke tempat tidur. Diraihnya terjemah Al-Qu`an lalu mulai membaca dengan suara pelan hampir tak terdengar. Setelah beberapa halaman dibacanya, Al-Qur`an diletakkan kembali di tempat semula, kemudian ia membaringkan tubuh dan kembali tertidur.
Pukul lima seperempat Vitlan bangun begitu mendengar suara ibu Icha membangunkan Saldin. Ia langsung ke kamar mandi, mengambil wudhuk. Kembali ke kamar untuk menunaikan shalat Subuh. Selesai shalat, ia membaca beberapa ayat Al-Qur`an, dilanjutkan dengan membaca buku.
Begitu dilihatnya hari telah mulai terang, ia melangkah ke luar rumah dan berjalan kaki di sepanjang jalan raya. Beberapa truk dan mobil pick up terlihat berlalu melewati jalan membawa muatan hasil laut.
Setelah puas berjalan kaki, Vitlan kembali ke rumah, kemudian mandi dan ganti pakaian. Ia mengambil sebuah buku dan beranjak ke beranda. Ia duduk membaca buku. Sesekali ia mengalihkan pandangannya ke jalan raya, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang dan anak-anak berseragam menuju ke sekolah.
”Tin tin tin,” terdengar bunyi klakson di depan rumah.
Bersamaan dengan munculnya Icha di depan pintu membawa Baki, berisi; sepiring pisang goreng dan sepiring ketan serta dua gelas teh manis, Saldin keluar dengan seragam sekolahnya. Hampir saja ia menumpahkan apa yang dibawa Icha.
”Eee Adin! hati-hati dik. Pelan-pelanlah,” kata Icha.
”Adin pergi sekolah ya Bang,” sapa Saldin sambil menggenggam tangan Vitlan dan menciumnya
”Ya Din,” jawab Vitlan, sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah Saldin.
Saldin bergegas turun tangga lalu naik ke boncengan, dan mereka pun berlalu.
”Hmm, kalau si Adin ini, gitu sajalah selalu, semua buru-buru,” omel Icha, sembari meletakkan piring dan gelas di atas meja, kemudian ia duduk di kursi sebelah kiri Vitlan.
”Namanya juga anak laki-laki yang sedang tumbuh,” jawab Vitlan, sambil tangannya mengambil pisang goreng.
”Abang waktu sebesar dia, kek gitu jugalah ya,” tanya Icha.
”Mmm lebih,” jawab Vitlan dengan mulut tetap mengunyah.
”Kek mana lebihnya Abang dulu?” tanya Icha.
”Yang namanya jatuh dari pohon, terjun dari tebing, dan jatuh dari sepeda, ndak kira lagilah, sudah puaslah,” jawab Vitlan.
”Iiihh ngeri kali Abang. Kok bisa sampai gitu? Abang pasti bandel waktu kecil ya,” tanya Icha lagi.
”Bukan bandel, tapi lasak,” jawab Vitlan enteng.
”Sama sajalah itu,” bela Icha.
”Be … bedalah, kalau bandel itu artinya tak mau dilarang. tak mau dikasih tahu, tapi kalau lasak, ya kek Adin tadi itu,” jelas Vitlan.
”Jatuh dari pohon apa saja pernah Abang?” selidik Icha.
”Seeering. … jatuh dari pohon Rambutan, pohon Jeruk, pohon Mangga, pohon Manggis, pohon kelapa,” jawab Vitlan.
”Terus yang dari tebing dan dari sepeda itu, bagaimana pula ceritanya itu?” tanya Icha lagi.
”Di dekat rumah Abang ada tebing, tingginya kira-kira sepuluh meter. Di bagian atas tebing itu banyak rumpun bambu. Di sana banyak menumpuk sampah daun-daunan dari pokok Embacang, Rambutan, Nangka dan jeruk Bali…
”Yok Bang, Icha, kita sarapan dulu,” sapa Cicik di depan pintu ruang dalam.
Vitlan menghentikan ceritanya lalu bangkit melangkah ke ruang dalam, mengikuti Cicik dan Icha. Selesai sarapan pagi, Vitlan kembali ke beranda dan duduk di tempat semula.
Sebenarnya ada keinginan di hatinya untuk berjalan-jalan di sekitar daerah itu, namun hasrat itu ditahannya demi mengingat tujuan utama kedatangannya ketempat itu. Ia tidak mau menafikan sedikitpun penderitaan batin yang sedang dialami Icha. Karena itu ia lebih memilih duduk-duduk saja di rumah, menemani Icha, daripada memenuhi hasrat keingintahuannya akan daerah itu.
Tak lama kemudian Icha dan Cicik datang bergabung bersamanya duduk di beranda. Bertiga mereka berbincang. Icha menatap Vitlan lembut, dan Vitlan membalas tatapan itu dengan senyuman.
”Lanjutkanlah Bang, cerita tadi,” rengek Icha.
”Cerita apa itu?” tanya Cicik.
”Cerita kenakalan bang Alan di waktu kecil,” jawab Icha.
”Waaah seru tuh. Kek mana tu ceritanya Bang,” timpal Cicik.
Vitlan merogoh kantong celananya dan mencari-cari sesuatu, keningnya mengerinyit. Icha coba memahaminya. Ia bangkit beranjak ke dalam dan keluar dari pintu samping yang menghubungkan dapur dengan halaman.
Tak berapa lama beselang Icha telah muncul kembali di beranda dengan sebungkus Ji Sam Soe berikut dengan korek api di tangan. Sembari duduk, Icha menyodorkannya ke depan Vitlan.
”Ini yang Abang cari kan?” katanya.
Vitlan menatap Icha kagum. Secepat itu, ia dapat memahami, apa yang dibutuhkannya. Dalam hati, Vitlan membatin,
“Sebegitu cepatnya, kau memahami apa yang kubutuhkan. Nampaknya kita memang ditakdirkan untuk bersatu. Abang berjanji padamu Icha. akan mendampingimu selamanya.”
Dia senyum dan meraih bungkus rokok itu, membelah dua bungkusnya dengan kukunya dan mengambil sebatang lalu menghisapnya.
”Ceritanya tadi sampai di mana ya?” tanya Vitlan.
”Tebing depan rumah yang ada bambunya,” jawab Icha.
”Ulangi dari awallah,” pinta Cicik, menyela.
”Kek mana ya? Sebenarnya ceritanya tak bisa diulang,” kata Vitlan menggoda.
”Aaach, tak enaklah sama bang Alan. Pilih kasih. Ulanglah Bang,” rengek Cicik.
Vitlan senyum-senyum melihat tingkah Cicik.
”Begini Cik, begini. Bang Alan itu waktu kecil nakal sekali. Suka manjat pohon dan main sepeda. Pohon apa saja dipanjati dan sering jatuh,” terang Icha.
”Iya Bang?” tanya Cicik.
Vitlan mengangguk, mengiyakan.
bersambung