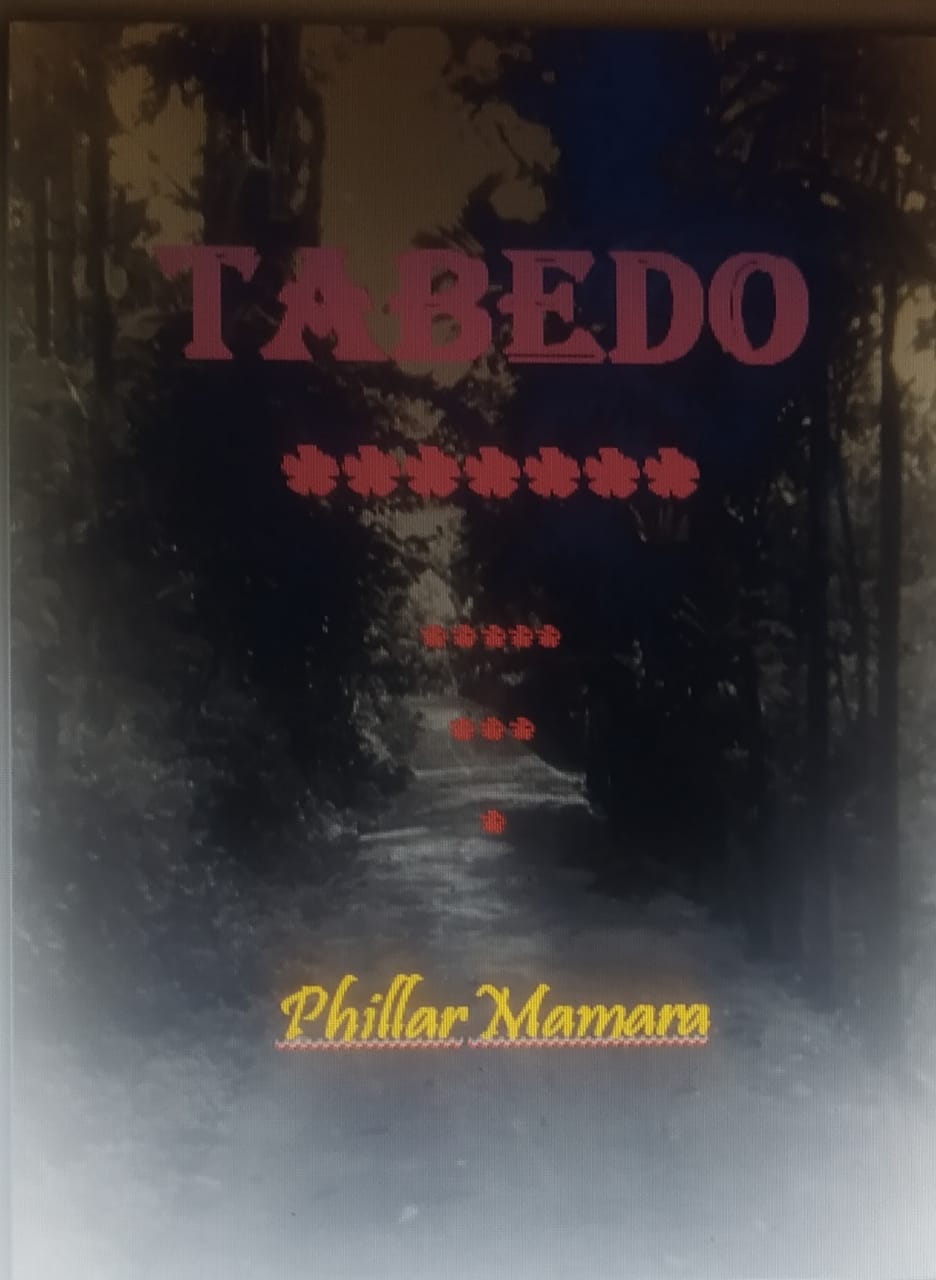Tabedo – Bagian 43
Oleh: Phillar Mamara
Bu Tina segera bangkit mendekat ke pintu lalu membukanya. Ia menyongsong bu Lela dan membantu mengangkat barang bawaannya. Vitlan berdiri menyusul ke teras, ikut membantu.
”Selamat ya, Lan. Berhasil masuk kelompok siswa berprestasi,” sapa bu Lela menyalami Vitlan.
”Makasih, Bu,” balas Vitlan.
”Ibu dengar, dapat prioritas masuk ke Ombilin ya?” tanya bu Lela, lagi.
”Iya Bu.” jawab Vitlan.
”Enaklah ya. Lulus ujian, langsung dapat tawaran kerja,” sambung bu Lela.
”Ya Bu. Tapi Alan masih ingin lenjut kuliah dulu, Bu,” jawab Vitlan.
”Ya, kalau bisa lanjut, bagus lanjut dululah pendidikannya. Nanti dapat kerjanya juga lebih baik,” katanya lagi.
”Teruskanlah ngobrolnya. Ibu masuk dulu,” lanjutnya, sembari beranjak ke bagian dalam rumah.
”Jadi kamu mau kuliah dulu, Lan? Bagaimana dengan tawaran kerja itu?” tanya bu Tina.
”Iyaaalah masak cuma tamat STM. Calonnya saja sarjana,” jawab Vitlan, sambil mengedipkan matanya pada bu Tina, yang membuatnya tersipuh.
”Kamu ingin kuliah di mana?” selidik bu Tina.
”Di mana bagusnya ya? Di Bandung apa di Jogja?” goda Vitlan.
”Jangan jauh-jauhlah Lan. Di Padang sajalah. Kan ada,” rengek bu Tina.
”Jurusan teknik terbaik itu, ada di Jawa,” sambung Vitlan.
”Jadi kamu mau pergi ke Jawa, Lan?” cemas.
”Bagaimana ya?” jawab Vitlan.
”Di Padang sajalah, Lan. Kan ada juganya jurusan teknik di FKIT-IKIP,” kata bu Tina.
”Tapi …” Vitlan belum sempat melanjutkan.
”Jangan tinggalkan akulah, Lan. Di Padang sajalah ya. Aku dapat mengunjungimu sesering mungkin,” kata bu Tina, menjangkau dan menggenggam erat tangan Vitlan.
Vitlan menangkap keseriusan di mata bu Tina. Untuk beberapa saat, ia terpaku di tempat duduknya, tanpa berusaha melepaskan genggaman bu Tina. Bu Tina meremas-remas tangan Vitlan, kemudian menempelkan ke dadanya. Ia takut sekali, bila Vitlan pergi jauh darinya. Vitlan merasakan gemuruh di telapak tangannya. Kemudian tangannya beralih memegang kedua pipi dan menatap mata Vitlan dalam-dalam. Vitlan membiarkan tangannya dan tangan bu Tina, tetap berada di tempat.
Ia mencoba mencari sesuatu, di bola mata yang mulai berair itu. Ia menangkap keseriusan dan kecemasan yang mendalam di sana. Vitlan berusaha mengusap air mata yang membasah di pipi bu Tina. Bu Tina mengambil tangan itu dan menempelkan ke mulutnya lalu mengecupnya lamat-lamat. Suasana menjadi hening dan sahdu.
Pelan, Vitlan menarik tangannya, kemudian menyadarkan kepalanya di sandaran kursi, sambil menatap langit-langit. Sementara itu, bu Tina beran-jak ke dalam. Beberapa saat berlalu, ia kembali lagi. Ia menghampiri Vitlan dan membelai rambutnya, lalu mengecup keningnya.
Suara adzan maghrib terdengar berkumandang dari radio. Vitlan bangkit dan merapikan pakaiannya, lalu berjalan ke pintu. Bu Tina mengiringi sambil memeluk pinggangnya.
”Lan, jangan tinggalkan ibu ya? Kamu kuliah di Padang saja, di FKIT-IKIP. Kamu dapat jadi guru teknik,” kata bu Tina, melepaskan pelukannya ketika mereka sudah sampai di depan pintu.
”Nanti Alan pikirkan masak-masak, mana yang terbaik,” kata Vitlan, terus melangkah keluar.
”E e, kapan kamu mau pergi?” tanya bu Tina, me-nahan tangannya.
”Lihat dulu, satu dua hari ini,” Lanjut Vitlan, sambil melangkah meninggalkan rumah tersebut.
Vitlan bergegas ke rumah kosnya. Sumarno didapatinya sedang menggosok pakaian.
”Banyak gosokanmu, No?” tanyanya
”Masih ado duo pasang lai,” jawab Sumarno.
”Jaan dimatikan, yo. Ambo mau menggosok pulo. Sabanta, ambo mandi dulu,” kata Vitlan, terus mengambil handuk dan bergegas ke sumur.
Selesai shalat maghrib, ia bawa gosokan itu keluar, guna membuang abunya dan me-nambahkan sedikit arang tempurung. Dengan menggunakan buku tulis, ia kipas-kipas arang tempurung itu, hingga menyala. lalu dengan menggunakan batang besi kecil, yang satu ujungnya dibengkokan, sebagai pegangan, ia ratakan sebaran bara yang berada di dalam gosokan tersebut, agar panas yang ditimbulkannya jadi merata, di dasar gosokan.
Satu jam kemudian, seluruh pakaiannya sudah siap digosok dan dimasukan ke dalam koper. Vitlan melayangkan pandangannya ke sekeliling kamar, mencari kalau-kalau masih ada yang belum dimasukan. Semua sudah masuk dan tidak ada yang tertinggal sama sekali. Ia menyulut sebatang kreteknya dan duduk lega di atas difan, selesai shalat Isya, ia keluar ke pasar Baru, cari makan malam dan ngumpul di tempat biasa teman-temannya nongkrong, di depan kedai Indra.
Di sana, sudah berkumpul: Gedek, Bahrum, Gito, Ical, Anto, Armen dan lainnya.
”Hai Lan,” sapa mereka serentak.
”Hai juga,” jawab Vitlan, sambil menghenyakan pantatnya di bangku kayu.
”Selamatlah Lan, tamat sekolah langsuang dapek karajo,” kata Gedek memulai percakapan.
”Selamatlah ya Lan,” kata Anto, Armen, Indra dan Ison.
”Dapek karajo di maa, Lan?” tanya Indra
”Si Alan ko, masuak 5 besar siswa terbaik STM. Dapek tawaran dari Ombilin, untuak bakarajo di sinan,” kata Bahrum.
”Oi mak. Baruntuang bana waang yo Lan. Salamat-lah sakali lai,” kata Anto dan Armen, bangkit mengulurkan tangan mereka.
”Bilo acara selamatannyo, Lan?” sambung Indra.
”Alun lai. Ambo masih pikia-pikia,” jawab Vitlan, menyambut uluran tangan kedua temannya itu.
”Apo juo ka dipikiakan lai,” sela Indra lagi.
”Ambo dimintak urang gaek jo uda ambo untuak kuliah dulu. Soal karajo, urusan mereka mancarikannyo,” jelas Vitlan.
”Di maa kuliahnyo, Lan?” timpal Indra.
”Uda ambo mintak di Jakarta,” jawab Vitlan.
”Lamak bana, hiduik waang, Lan. Bilo ka sinan?” lanjut Indra.
”Alun tantu lai, Ndra. Caliak babarapo hari ka muko ko dulu,” jawab Vitlan.
.
Selesai ngobrol ngalar ngidul ke sana ke mari, bersamaan pula dengan usainya bioskop, mereka ikut membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Di ujung jembatan, Gedek dan Bahrum memisahkan diri. Vitlan dan Indra berjalan beriringan berdua, menuju tempat tinggal mereka di Kubang Sirakuak.
Tiba di kamar, setelah berganti pakaian, Vitlan membaringkan tubuhnya di dipan. Ia menyulut kreteknya yang masih panjang. Pikirannya mengembara dari, tawaran kerja, kuliah, bu Tina dan Emi yang pergi meninggalkannya begitu saja. Lain dari itu, ia ingin pergi sejauh-jauhnya dari keluarganya. Vitlan menyalakan ji sam soenya sebatang lagi. Malam semakin larut. Pikirannya pun larut dalam kebingungan dan angan-angan. Ia tak ingin kekecewaan, sakit hati, dendam menumpuk di dalam dada dan kepalanya. Vitlan ingin membawa kegalauan hati dan derita jiwanya, sejauh-jauhnya ke satu tempat di mana ia dapat mengubur semuanya dan mulai membangun kehidupan baru.
Dalam kelelahan jiwa, raga dan pikiran, akhirnya Vitlan terkulai tidur dengan puntung rokok masih menempel di sela jarinya. Ia baru terbangun, tatkala pintu kamarnya digedor-gedor dari luar, dan namanya dipanggil-panggil. Ia segera bangun menuju pintu lalu membukanya.
”Masuk, Bes. sebentar ya,” katanya beranjak ke kamar mandi.
”Apa yang kau kerjakan tadi malam, makanya jam segini baru bangun, kau?” tanya Besra, teman sekelasnya.
”Tak ada. Cuma mataku yang tidak mau tidur, tadi malam,” jawab Vitlan, sambil duduk bersandar ke dinding di atas difan.
”Apa yang kau pikirkan rupanya?” tanyanya lagi dengan logat Bataknya.
”Tak ada. Cuma bingung saja,” jawab Vitlan.
”Apa rupanya yang kau bingungkan. Tamat sekolah pekerjaan sudah menunggu. Apalagi,” tandas Besra.
”Itulah masalahnya, Bes. Aku masih ingin kuliah. Cuma aku bingung, mau kuliah di mana. Mama, kakak dan udaku, nyuruh aku kuliah di Jakarta. Sementara aku ndak ingin dekat dengan saudara. Aku ingin mandiri, jauh dari keluarga, sehingga aku bebas melakukan apa saja, sesuai kemauanku,” jelas Vitlan.
”Kalau di Padang, tidak uji kau kuliah?” tanya Besra.
”Di Padang lagi. Sedang di Jakarta saja aku ndak mau. Lagi pula, jurusan teknik Cuma ada di IKIP,” bela Vitlan.
”Kalau begitu, kau kuliah di Medan saja. Di sana ada USU dan ITS. Satu negeri satu swasta,” kata Besra.
(Vitlan tercenung, kemudian manggut-manggut) ”Betul juga yang kau katakan itu, Bes. Medan ya. Di sana ndak ada saudaraku, memang. Aku pernah ingin ke sana,” kata Vitlan.
”Medan itu, kotanya indah, jalan-jalan utamanya dipenuhi pohon rindang, sejuk, sampai di gelar Paris van Sumatera,” papar Besra.
”Kau pernah tinggal di Medan rupanya?” tanya Vitlan.
”Aku tinggal di Tarutungnya. Cuma aku pernah ke sana beberapa kali,” bela Besra.
”Kau sendiri, selesai dari sini, ke mana?” tanya Vitlan.
”Tergantung ito akulah. Ke Medan katanya, ke Medan aku. Di sini katanya, di sini aku,” jawab Besra.
”Kok gitu katamu,” tanya Vitlan.
”Iyalah. Aku ke sini kan dibawa itoku.. jadi ke mana ia pergi, ke situ pula aku,” jelas Besra.
”Ooo, gitu,” kata Vitlan.
”Sudah ya, Lan. Aku permisi dulu,” kata Besra mohon diri.
”Mau ke mana kau, Bes?” tanya Vitlan.
”Mau ke pasar dulu. Ya Lan, kalau jadi ke Medan kasih tahu aku ya?” kata Besra, sambil berlalu.
:Baik, nanti kukabari,” jawab Vitlan, melambaikan tangan.
Sepeninggal Besra, Vitlan berandai-andai sendirian. Andai kuliah di Jakarta, banyak saudara dan kerabat. Ndak bisa bebas. Andai kuliah di Padang, dekat dengan kampung dan keluarga, juga ndak bebas. Bekerja di Ombilin dan kawin dengan bu Ti-na. Punya keluarga, punya anak dan jaminan hidup. Tapi ndak mungkin dapat restu dari orang tua. ”Aku harus pergi jauh dan menghapus masa laluku,” katanya membatin. Medan, ya Medan. Satu-satunya tujuan untuk menghindari semuanya.
Vitlan tersenyum, telah mendapat jalan keluar, untuk masa depannya. Ia melirik kompor dan memeriksa minyaknya, ada. Ia segera memasak nasi sekenanya, karena temannya, Sumarno telah pulang ke kampung tadi pagi. Siap masak nasi, Vitlan pergi ke pasar baru untuk membeli lauk.
Siang itu, Vitlan dengan lahap. Nasi yang ia masak untuk dua kali makan, hampir habis disantapnya. Selesai makan, ia pantik sebatang rokok dan keluar duduk di bangku di bawah rambutan di halaman rumah induk. Sebatang habis lalu disambung dengan batang kedua. Hembusan angin sepoi-sepoi, membuatnya beberapa kali menguap. Tak tahan diserang kantuk, Vitlan beranjak ke kamar dan merebahkan badannya di atas dipan. Sebentar kemudian, ia langsung tertidur dengan lelapnya.
Suasana gerah di dalam kamar, membuat Vitlan terbangun. Ia lantas mencuci muka ke sumur, kemudian mengganti baju dengan kaos katun putih bertuliskan Levi’s. Melalui jalan belakang rumah yang teduh oleh rerimbunan pohon, Vitlan melangkahkan kakinya ke pasar baru. Di atas jembatan di sisi rel kereta api, ia berhenti memandangi jernihnya air sungai Lunto, mengalir membelah kota. Beberapa ikan kecil, terlihat dengan jelas, berenang di dalam air. Ia terus berjalan menuruni tangga, masuk ke dalam pasar yang kosong karena telah usai. Deretan kios tertutup satu persatu dilewatinya, hingga kemudian sampai di depan kios Indra.
bersambung