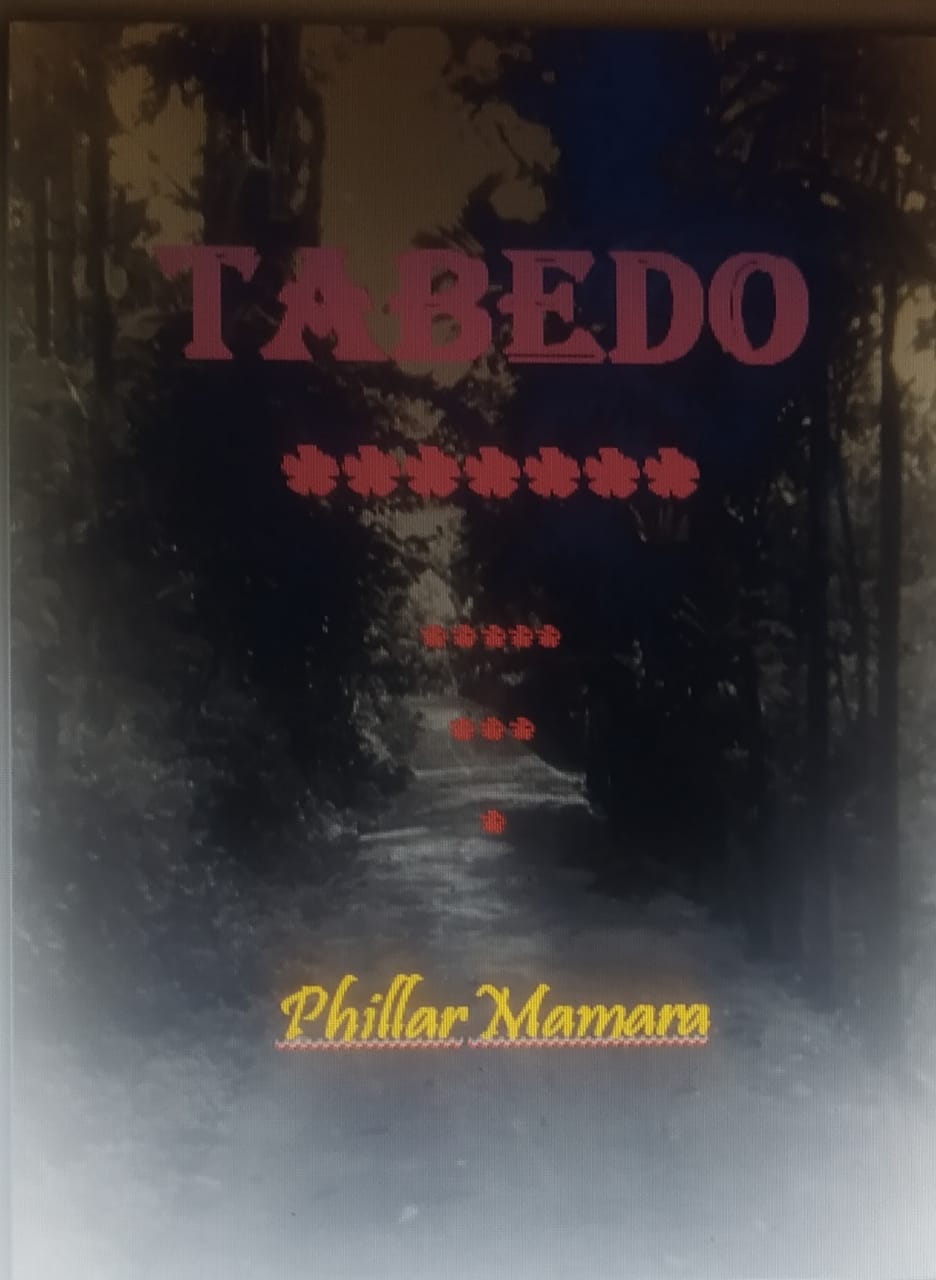Tabedo – Bagian 8
Oleh: Phillar Mamara
Darah Vitlan berdesir mendengar pernyataan Cicik. Ia melirik Icha, keduanya beradu pandang. Vitlan terkesiap, jantungnya berdebar keras.
“Esok atau lusa abang datang, insya Allah,” bela Vitlan.
“Besok Icha sudah pulang kampong,” sambung Raudah.
“Oh ya,” seru Vitlan terpelongoh.
“Makanya kami datang ke sini,” sambung Cicik,
Icha mendongak, kembali mereka bertatapan. lalu menunduk mengalihkan pandangannya ke gelas yang sedari tadi dipegangnya. Vitlan mencoba memandangi wajah Icha dalam-dalam.
Di sana ia melihat keteduhan.
Keteduhan hati seorang gadis yang tulus, apa adanya. Vitlan mencoba memperhatikan gadis itu secara sungguh-sungguh. Ada simpati di hatinya, ada ketertarikan di sana.
“Icha sudah mau pulang ke kampung?” sapa Vitlan.
“Iya, rencananya besok naik kereta api,” jawab Icha sembari menatap Vitlan, kemudian tunduk.
Bisu sesaat, kemudian,
“Icha datang ke sini ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongan Abang tempo hari kepada kami, sekaligus minta maaf bila kedatangan kami telah mengusik ketenangan Abang,” kata Icha perlahan.
“Ndak ndak, Abang senang kok kalian datang,” bela Vitlan tergagap.
“Tapi Mak Abang bilang, Abang tak…”
Refleks tangan Vitlan bergerak ke muka Icha dan jarinya menempel di mulat Icha,
“Sudah sudah sudah, jangan diteruskan,” potong Vitlan.
Icha kaget, yang lain kaget, Mak pun kaget melihat apa yang dilakukan Vitlan. Mereka terperangah, Vitlan sadar dan segera menarik tangannya.
“Maaf maaf, Abang ndak sengaja,” pintanya dengan gugup.
Waktu telah menunjukkan pukul 09.50 WIB. Malam.
“Waktu sudah mulai larut, yok Abang antar kalian, nanti ibuk kecarian,” kata Vitlan setelah dapat menguasai gejolak perasaannya.
“Ayok,” jawab mereka serentak.
Vitlan segera berjalan keluar ke trotoar dan memanggil becak yang parkir tidak jauh dari tempat ia berdiri.
“Mak Udin, Bang Ucok, sini,” kata Vitlan kepada dua abang becak yang memang sudah dikenalnya.
Kedua abang becak segera menghampirinya,
“Mau ke mana Lan,” sapa mak Udin.
“Amaliun Mak,” jawab Vitlan.
“Ngantar cewek nih Lan,” gurau Mak Udin.
“Tenanglah mak Udin,” jawab Vitlan
“Buk kami permisi pulang ya buk,” kata ketiga gadis seraya satu persatu dari mereka menyalami mak.
”Mak, Alan pergi sebentar ya,” kata vitlan pada Mak.
“Hati-hati ya,” jawab Mak sambil berdiri di depan kedai
Cicik dan Raudah segera naik ke becak bang Ucok, Icha naik ke becak mak Udin. Vitlan berdiri bengong. Ia bimbang harus sebecak dengan Icha.
“Nunggu apa, Lan?” sapa mak Udin.
“Ndak ada, Mak,” jawab Vitlan.
“Udah, ayok naik,” tegur mak Udin, yang membuat Vitlan tergagap dan segera naik ke becak mak Udin seraya berkata
“Ayok Mak,” katanya.
Jalanan mulai sepi, di atas becak hening. Dada Vitlan bergemuruh begitu hawa panas yang berasal dari tubuh Icha yang menempel rapat ke tubuh-nya, mengalir ke seluruh tubuhnya. Vitlan mencoba memejamkan mata menenangkannya, namun gemuruh itu semakin membakar dan menggoncang dada nya.
“Bang Alan, maafkan Icha ya, bila telah mengganggu ketenangan Abang,” kata Icha lirih, meme-cah keheningan.
“Ndak apa-apa kok,” jawab Vitlan gagap.
“Tapi Abang kelihatannya gusar sekali, Abang marahkan kami datang,”, balas Icha.
“Ndak ndak, bukan begitu, Abang hanya tak tahu harus berbuat apa,” bela Vitlan.
“Abang takutkan bila gadis di seberang jalan itu tahu dan marah melihat kami datang ke rumah Abang,” sungut Icha sembari memperbaiki letak duduknya, yang membuat tangannya, secara refleks berhimpitan dengan tangan Vitlan.
Vitlan membiarkan tangan itu. Icha pelan-pelan berusaha menarik tangannya dari atas tangan Vitlan. Tapi spontan Vitlan menggenggam tangan itu, kemudian membawanya ke pangkuannya. Icha diam membiarkan tangannya digenggam erat Vitlan. Ia memejamkan mata dan berusaha menikmati genggaman itu, hangat. Hatinya berbunga dan ia serasa melayang-layang di langit tinggi.
“Icha, Abang takut, Abang ndak punya siapa-siapa,” kata Vitlan sambil mencoba melepaskan genggamannya dan berusaha mencari sesuatu di mata Icha di keremangan cahaya lampu jalanan. Icha malah semakin mempererat genggaman tangannya pada tangan Vitlan. Ia tak menyangka Vitlan berkata demikian, ia merasa bersalah.
“Maafkan Icha ya Bang, kalau kata-kata Icha menyinggung perasaan Abang,” pinta Icha.
“Ndak apa-apa, Abang hanya takut nantinya Icha kecewa,” balas Vitlan.
Becak yang mereka tumpangi telah sampai di depan pintu pagar rumah Cicik. Cicik mengeluarkan uang dari dompet untuk membayar ongkos becak, tapi Vitlan mencegahnya,
“Biar Abang saja yang bayar,” kata Vitlan.
“Tidak, biar Cicik saja, kan kami yang datang ke rumah Abang,” bela Cicik sambil menyerahkan uang kepada bang Ucok dan berlalu ke depan pintu.
“Assalamu’alaikum, buk, buk,” panggil Cicik pada ibunya.
“Wa’alaikumussalam,” jawab ibu Cicik seraya membukakan pintu.
Vitlan turun dari becak diikuti oleh Icha. Ia berusaha melepaskan genggaman dari tangannya. tapi Icha malah mempererat genggamannya. Ia baru melepaskannya ketika melihat ibu Cicik membukakan pintu buat mereka.
“Masuk dulu nak Alan,” sapa Ibu Cicik ramah, begitu melihat Vitlan ada di antara mereka.
“Terima kasih buk, sudah larut, lain kali saja, permisi buk, Assalamu’alaikum,” jawab Vitlan
“Wa’alaikumussalam,” jawab mereka.
“Kok lama sekali pulangnya,” sapa Ibu Cicik kepada anak-anaknya beberapa saat setelah mereka duduk.
“Panjang ceritanya Buk,” jawab Cicik.
“Sudah, kalau begitu kalian makanlah dulu, sudah malam kali ni. Nanti kalian sakit,” Sambung Ibu.
“Kami sudah makan Buk, di sana. Kami makan nasi goreng, bang Alan yang bikin. Masakannya enak sekali, dia pintar masak Bu,” kata Cicik, menyerocos.
“Ahh… yang benar, masak anak lajang pandai masak,” tangkis ibu.
“Benar Buk, si Icha saja yang biasanya makannya sikit, habis sepiring besar,” bela Cicik dengan memonyongkan mulutnya sembari mengembangkan kedua telapak tangannya dengan posisi saling berhadapan.
“Sudah, sudah, coba kamu ceritakan dari awal bagaimana ceritanya,” Sela ibu.
bersambung