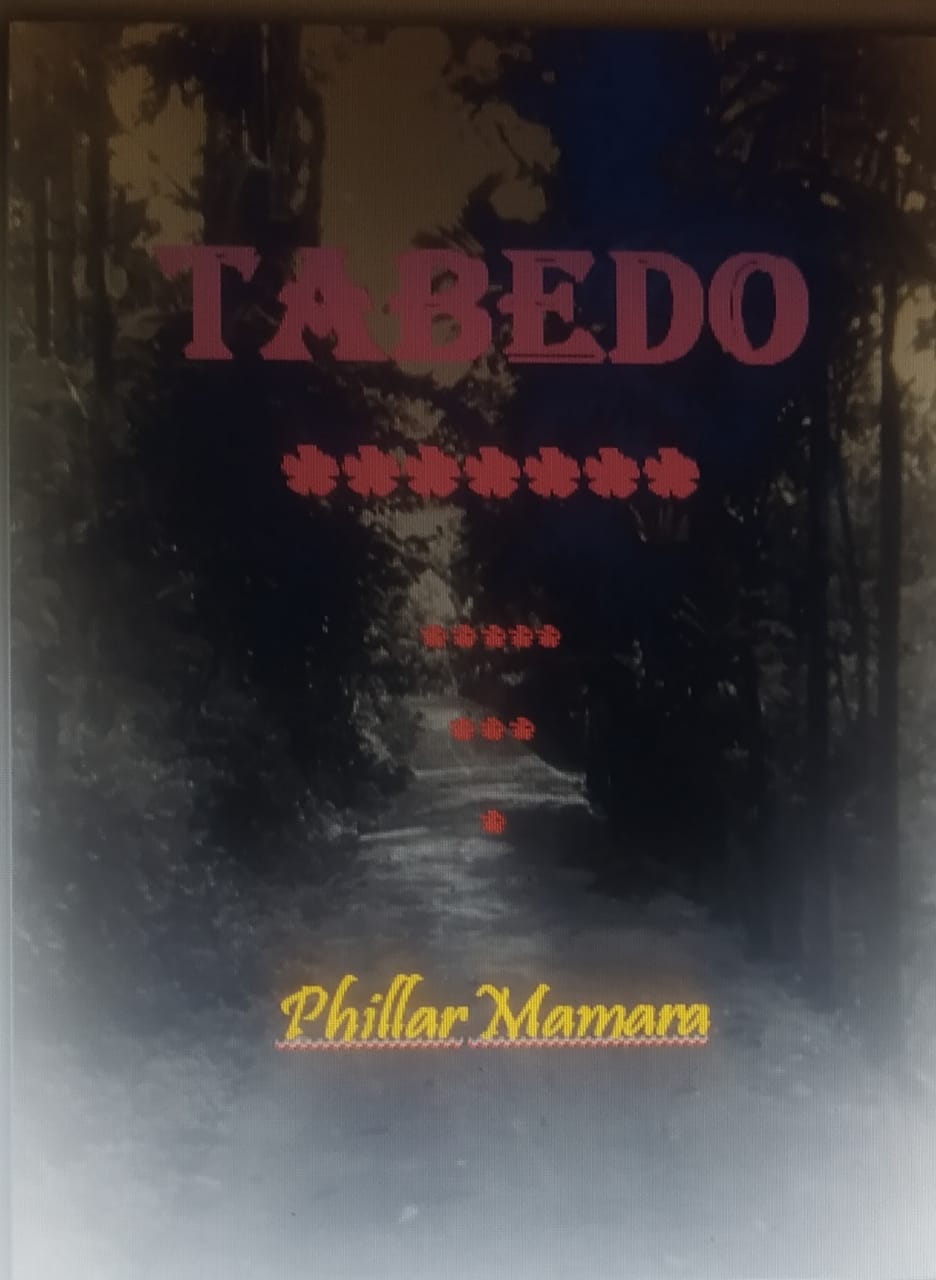Tabedo – Bagian 9
Oleh: Phillar Mamara
“Begini ceritanya Buk, setelah kami sampai di alamat, ternyata rumah bang Alan itu adalah sebuah rumah makan. Kami disambut oleh Mak abang itu. Sewaktu kami tanyakan bang Alan ada apa tidak, Maknya bilang bang Alan belum pulang kuliah. Ternyata bang Vitlan itu mahasiswa Buk,” kata Cicik.
“Terus,” kata ibu.
“Terus, Maknya bilang biasanya habis maghrib ia sudah pulang. Jadinya kami tunggu.”
“Oohh… jadi karena asyik cerita, kalian lupa pulang, begitu,” sambung ibu.
“Bukan begitu Buk, bang Alannya baru datang jam setengah Sembilan,” bela Raudah.
“Sambil menunggu bang Alan kami cerita-cerita sama Maknya, ia bilang bang Alan itu, orangnya tak pernah akrab dengan perempuan. Ia heran kok kami bisa dekat dengannya, sampai-sampai mau mengantar segala. Pada hal gadis cantik yang tinggal di seberang rumahnya sudah lama tergila-gila dan berusaha mendekatinya, tapi tak pernah digubrisnya,” jelas Cicik.
“Betul Buk, anaknya cantik sekali, anak orang kaya lagi,” timpal Raudah.
“Ah masak,” sela ibu.
“Benar Buk, Raudah percaya apa yang dibilang Mak bang Alan itu, soalnya bang Alan itu bukan anak kandung ibuk itu. Dia itu anak angkat ibuk itu,” timpal Raudah.
“Benar Cik, Ibuk itu bilang bang Alan itu sudah lebih 4 tahun tinggal di situ. Mulanya ia indekost, tapi karena ia rajin membantu semua pekerjaan, mulai dari mencuci piring, masak, membuka dan menutup kedai sampai belanja ke pajak, lama-kelamaan ia diangkat ibuk itu jadi anak angkatnya,” sambung Icha.
“Alaaa … mentang-mentang …,” goda Cicik tanpa meneruskan ucapannya.
“Kan iya gitu, dibilang ibuk itu,” bela Icha, sembari beranjak dari tempat duduknya mendekati Cicik, namun Cicik segera berdiri dan menjauh. Icha menjadi geram dan berusaha mengejar.
“Sudah sudah, kayak anak kecil saja kalian,” kata ibu sambil senyum-senyum melihat tingkah anak-anak dan keponakannya yang sudah beranjak dewasa itu.
“Iya, Anak ini bikin orang sebel saja,” kata Icha menghentikan langkahnya.
Ibu Cicik melirik keponakannya yang salah tingkah. Ia mencoba menangkap apa yang sedang terjadi padanya melalui perubahan sikap dan perilakunya sejak mengenal Vitlan. “Keponakanku sudah besar,” bisiknya dalam hati sambil senyum memperhatikan Icha, yang
“Anak-anak, sudah hampir jam sebelas, ayo tidur biar tidak terlambat bangun,” seru ibu Cicik kepada ketiga anak gadisnya.
‘Ya Bu, ya Cik’, jawab mereka bersamaan seraya beranjak dari ruang tengah.
Mereka berjalan ke belakang, Cicik masuk kamar mandi lebih dulu, lalu langsung ke ruang shalat. Icha shalat paling belakangan. Selesai shalat Cicik langsung ke kamar dan berganti pakaian dengan piyama. Tak lama berselang Raudah masuk.
Setelah agak lama Icha belum muncul juga di kamar, Cicik beranjak keluar dan mendapati Icha masih bersimpuh di atas sajadah menengadahkan tangan berdo’a ke hadirat Tuhan. Cicik menatapnya tekun. Rona wajah Icha kadang senyum dan kadang serius dalam berdo’a. Sifat usilnya muncul.
Dengan sedikit mengeluarkan suara mulutnya mulai berkomat-kamit.
“Ya Tuhan, terima kasihku kepadaMu yang telah mempertemukan daku dengan seorang pria tampan lagi baik hati. Ya Tuhan kumohon kepadaMu agar kebahagiaan yang mulai bersemi di hati hamba ini akan mekar dan berkembang selamanya.”
Icha mencoba tak peduli, Cicik menggoda lagi.“Ya Tuhanku, hamba tak menyangka akan bertemu lelaki yang telah membuat jantung hamba selalu berdebar dan tak dapat memejamkan mata meski malam telah larut. Ya Tuhanku …
“Aduh,” Cicik mengaduh begitu sebuah cubitan mampir di rusuknya. Cicik tak menyangka kalau Icha telah selesai berdo’a.
“Rasakan, mulut usil,” kata Icha geram.
Cicik balas mencubit, tapi Icha keburu lari ke kamar. Cicik mengejar sampai ke kamar. Tapi Icha telah menunggu dengan tangan digenggam dengan posisi siap mencubit.
“Ayo mendekat, biar kena ini lagi hhmm,” tantang Icha sambil menggeretakkan giginya.
Cicik tak jadi mendekat. Sambil meringis ia duduk di tepi ranjang lalu menaikkan baju piyamanya melihat bekas cubitan Icha. Sambil mengusap-usap bekas cubitan tersebut ia berucap,
“Cubitan anak ini keras kalilah, lihat nih sampai biru,” ringis Cicik sambil memperlihatkan rusuknya.
“Salah sendiri, makanya mulut itu dijaga,” kilah Icha sebal.
“Awas nanti ya,” ancam Cicik sewot.
“Oouw, ngancam ya. Boleh saja, biar biramnya mau ditambah lagi,” balas Icha enteng sambil mendekat.
“Tidak tidak, tidak jadi,” balas Cicik merendah.
Sesaat kemudian ketiganya sudah merebahkan diri di atas kasur.
Malam itu Icha bermimpi berjalan-jalan di sebuah taman di lereng bukit di mana banyak sekali bunga-bunga indah sedang mekar. Ia berjalan kian kemari dari sekuntum bunga ke kuntum bunga yang lain. Setiap ia sampai di tanaman bunga yang berbeda, dipegangnya bunga tersebut lalu diciumnya dalam-dalam sembari menengadahkan wajah sehingga kelihatan jelas lehernya yang jenjang. Ia mendaki dan mendaki hingga sampai di bagian atas bukit.
Di atas bukit tersebut terdapat sebuah dangau yang beratapkan daun nyiur dan berlantaikan batang pinang yang ditetak. Ia melangkah naik, akan tetapi sebelum sampai di atas dangau,
“Aduh,” Icha menjerit perlahan ketika ia merasa ada yang menusuk di pipinya.
Icha memegang pipinya dan mencabut tusukan tersebut. Bekas tusukan tersebut terasa perih dan gatal. Icha menggaruknya. Pipinya makin lama makin gatal dan kemudian warna pipinya yang putih kemerahan perlahan berubah menjadi merah tua. Bintik-bintik merah kekuningan dan berair mulai menyembul dari bawah kulit yang kemudian secara cepat menebar hampir memenuhi sebelah pipinya.
bersambung